Dahlan dan Sepatu Peradaban
Inilah kisah
tentang sepatu. Kisah perihal cita-cita sederhana seorang bocah dari keluarga
miskin di pelosok Magetan, Jawa Timur, yang ingin memiliki sepasang sepatu.
Mengingatkan kita pada kemauan keras seorang siswa sekolah dasar di Iran guna mendapatkan
sepatu, dalam film The Children of Heaven
(1997), karya Majid Majidi. Berbeda dari film asing berdurasi pendek itu, Sepatu Dahlan adalah novel panjang yang diangkat
dari tarikh kemiskinan masa silam seorang menteri bersahaja, yang dalam
pertemuan-pertemuan penting sekalipun, tetap melenggang dengan sepatu kets, bahkan
saat menghadap presiden di istana negara.
Ia adalah Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos Group, yang kemudian dipercaya
menjadi Dirut PLN, dan kini berlabuh di kursi menteri BUMN. Dahlan tak henti-henti menjadi perhatian,
bukan karena dugaan korupsi sebagaimana yang menimpa sejumlah pejabat teras di
republik ini, melainkan karena prestasi kerja, komitmen dan ketegasan sebagai
pemimpin kementerian strategis, dan etos kebersahajaan yang dipandang nyentrik
di kurun yang silau oleh budaya ewuh-pakewuh dan basa-basi. Dahlan satu-satunya
menteri yang nyaris ditolak oleh paspampres sebelum memasuki ruang rapat
kabinet di istana Bogor, lantaran ia datang dengan ojek. Untunglah seseorang tergesa
meneriakkan bahwa laki-laki yang baru turun dari ojek itu adalah seorang menteri.
Dahlan pula menteri yang bisa lahap menyantap soto atau gado-gado di warung
kaki lima, dan menginap di rumah warga dalam sejumlah kunjungan kerja, yang
tentu jauh dari fasilitas, apalagi layanan bagi orang sekaliber menteri.
Dikisahkan,
sejak duduk di bangku SR (Sekolah Rakyat) hingga tsanawiyah dan aliyah di
pesantren Sabilul Muttaqien, Takeran,
Dahlan bersekolah tanpa sepatu alias nyeker. Mungkin itu sebabnya, segala
bentuk ikhtiar guna mendapatkan sepatu menjadi perhatian utama novel setebal 369
halaman ini. Cerita dibuka dengan ketegangan sebelum Dahlan menjalani operasi
transplantasi hati lantaran penyakit liver yang dideritanya. Masa lalu yang kembali terngiang dalam kenangan Dahlan
setelah suntikan pembiusan menjadi pintu masuk bagi pengarang guna menyingkap detail-detail
riwayat masa kecil Dahlan; sejumlah
peristiwa memalukan di kebun tebu, keinginan bersekolah di SMP Magetan (bukan di
pesantren Takeran), horor sumur tua Cigrok¾tempat pembuangan mayat di
masa kuasa PKI Madiun 1948¾dua ekor domba yang direlakan sebagai ganti-rugi sepeda
teman yang rusak, kematian ibu yang sangat tiba-tiba, dan tentu saja; keinginan
besar untuk memiliki sepatu.
Dalam sebuah
diskusi, Khrisna Pabichara mengakui penulisan novel ini terbilang sangat bergegas,
karena penerbit tampaknya tidak mau kehilangan momentum. “Mumpung tokohnya
sedang bertabur bintang”. Meski begitu,
hingga resensi ini ditulis, angka penjualan Sepatu
Dahlan terus melejit dan sudah
memasuki memasuki cetakan keempat. Seorang pembahas dalam perbincangan yang
lain, dengan nada sinis mengatakan; “Sepatu
Dahlan laku keras bukan karena mutu kenovelannya, tapi karena jaman telah memilihnya,
sebagaimana jaman memilih Jokowi ketimbang Foke dalam pilkada DKI”. Ada
benarnya sinisme itu, sebab pola-pola penceritaan yang dirancang pengarang rasanya
terlalu biasa, bahkan pada bagian-bagian tertentu terlalu memaksakan. Suasana
pesantren Sabilul Muttaqien, 1961, yang
lebih banyak dideskripsikan dengan sepak-terjang dan kebolehan Dahlan sebagai
pemain inti dalam tim bola Volly mengesankan suasana pergaulan antarsantri di
lingkungan pesantren masa kini. Sama sekali tidak tercium aroma kitab kuning,
ungkapan-ungkapan khas bahasa Arab yang di masa itu tentu amat kaya dengan
rujukan ilmu bayan, ma’ani, dan badi’. Lebih dari separuh novel ini dihabiskan oleh
pengisahan tentang Dahlan, Kadir, Fadli, Arif dalam tim bola Volly pesantren Takeran,
yang bila kurang sabar, akan sangat menjemukan.
Tengok pula peristiwa kedatangan juragan
Akbar ke rumah orangtua Dahlan setelah Dahlan dituding merusak sepeda Maryati,
teman sekolahnya. Entah karena penuh tanggung jawab atau karena tersinggung,
ayah Dahlan menyerahkan dua ekor domba
sebagai ganti rugi. Ayah Dahlan sanggup membayar ganti rugi sepeda dengan harga
mahal, tetapi kenapa ia begitu enggan membelikan sepatu bagi anaknya? Padahal,
jarak antara Kebon Dalem dan Takeran lebih kurang 12 km perjalanan
pulang-pergi. Bisa dibayangkan betapa melepuhnya kaki Dahlan karena nyeker
setiap hari. Muncul kesan bahwa cita-cita memiliki sepatu yang tak kunjung
kesampaian bukan karena etos berhemat keluarga Dahlan, melainkan karena kepentingan
hendak membangun efek dramatik cerita. Bukankah Dahlan punya kakak perempuan bernama
Shofwati yang sedang berkuliah di Madiun? Sebagai wakil dari tokoh terdidik,
tentu tidak mungkin Shofwati membiarkan adiknya nyeker selama bertahun-tahun.
Setidaknya ia bisa meyakinkan orangtuanya bahwa sepatu lebih penting dari
sepeda.
Diceritakan
pula bahwa Dahlan adalah anak yang kerap melampiaskan penyesalan dan kekecewaan
pada lembaran-lembaran buku diary. Di era tahun 60-an, mungkinkah seorang anak
miskin, yang saban hari disibukkan oleh pekerjaan mengembalakan domba dan
karena deraan kelaparan kerap tertangkap basah mencuri tebu, bisa akrab dengan
buku harian? Rasanya jauh panggang dari api. Meski begitu, hampir di setiap
bab, pengarang menyelipkan kutipan catatan harian Dahlan, hingga muncul kesan
bahwa pola-pola semacam itu tampaknya telah menjadi siasat pengarang tatkala
kehabisan bahan, sebagaimana yang sering ditemukan dalam novel-novel yang
pengarangnya terobsesi untuk sekadar menjadi buku tebal, supaya tampak rinci
dan serius.
Romantika masa muda Dahlan yang menjatukan
pilihan pada Aisha, anak gadis mandor perkebunan tebu agaknya dapat menjadi penggalan
kisah yang dapat membuai pembaca, meski waktu penceritaan tidak terbuhul
sebagaimana mestinya. Perpindahan waktu dari masa tsanawiyah ke masa aliyah meloncat
begitu saja, tanpa menyuguhkan peristiwa-peristiwa yang dapat menjembataninya.
Aisha yang menyatakan cintanya pada Dahlan lewat surat yang sekaligus
berpamitan karena gadis itu akan berkuliah di Yogyakarta, cukup mengagetkan. Sebab,
narasi tentang hubungan mereka hampir semuanya terjadi ketika sekolah Dahlan
masih di tingkat tsanawiyah dan Aisha masih di SMP Magetan.
Memang tidak gampang menulis novel dari
riwayat seorang tokoh yang sedang berkilau cahaya. Pengarang bisa terjebak
dalam ungkapan-ungkapan prosaik bergelimang decak-kagum, atau terancam oleh
kemarahan lantaran menyingkap hal-ihwal tak terlihat yang boleh jadi mencemari
keterpujian tokoh tersebut. Khrisna
Pabichara tampaknya telah selamat dari dua jebakan itu. Dahlan akhirnya meraih
cita-cita punya sepatu. Dengan sepatu baru ia meninggalkan Kebon Dalem,
bertolak menuju Samarinda, menyongsong masa depan. Tapi anehnya, sejak itu, dan
sebagaimana Dahlan Iskan masa kini, justru tidak memperlakukan sepatu sebagai
pertanda pencapaian, tapi sebagai lambang kesederhanaan. Dalam sebuah
perbincangan, seorang teman menyebutnya; sepatu peradaban…
DATA BUKU
Judul : Sepatu Dahlan
Penulis : Khrisna Pabhicara
Penerbit : Noura Books, Jakarta
Cetakan : I, Mei
2012
Tebal : 369 halaman
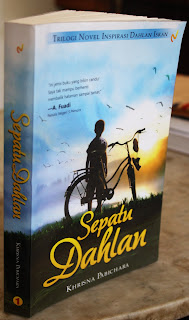


Comments
salam