Gabo, Mario, dan Beban Berat Masa Lalu
Damhuri Muhammad
Mexico City, 12 Februari 1976. Di pelataran sebuah gedung bioskop, sebelum pemutaran perdana film Supervivientes de los Andes karya Rene Cardona, Mario Vargas Llosa, sastrawan Peru, melihat kedatangan Gabriel Garcia Marquez. Tanpa bertanya-tanya, dan tak begitu terang apa pasalnya, Llosa seketika saja melayangkan bogem mentah ke wajah Garcia Marquez, hingga novelis Kolumbia itu ambruk dibuatnya. Seorang teman tergesa-gesa lari ke kios daging tak jauh dari situ, ia mengambil seiris daging lalu menempelkannya di mata Gabo (panggilan akrab Garcia Marquez) yang lebam sebagai kompres. Seorang fotografer sempat memotret Gabo dengan mata kiri babak belur, tetapi foto itu baru dilansir 30 tahun kemudian, oleh koran kiri Meksiko la Jornada, edisi 6 Maret 2007 saat pers Amerika Latin ramai mengabarkan kondisi mutakhir maestro sastra "realisme-magis" yang sudah sepuh dan sakit-sakitan itu.
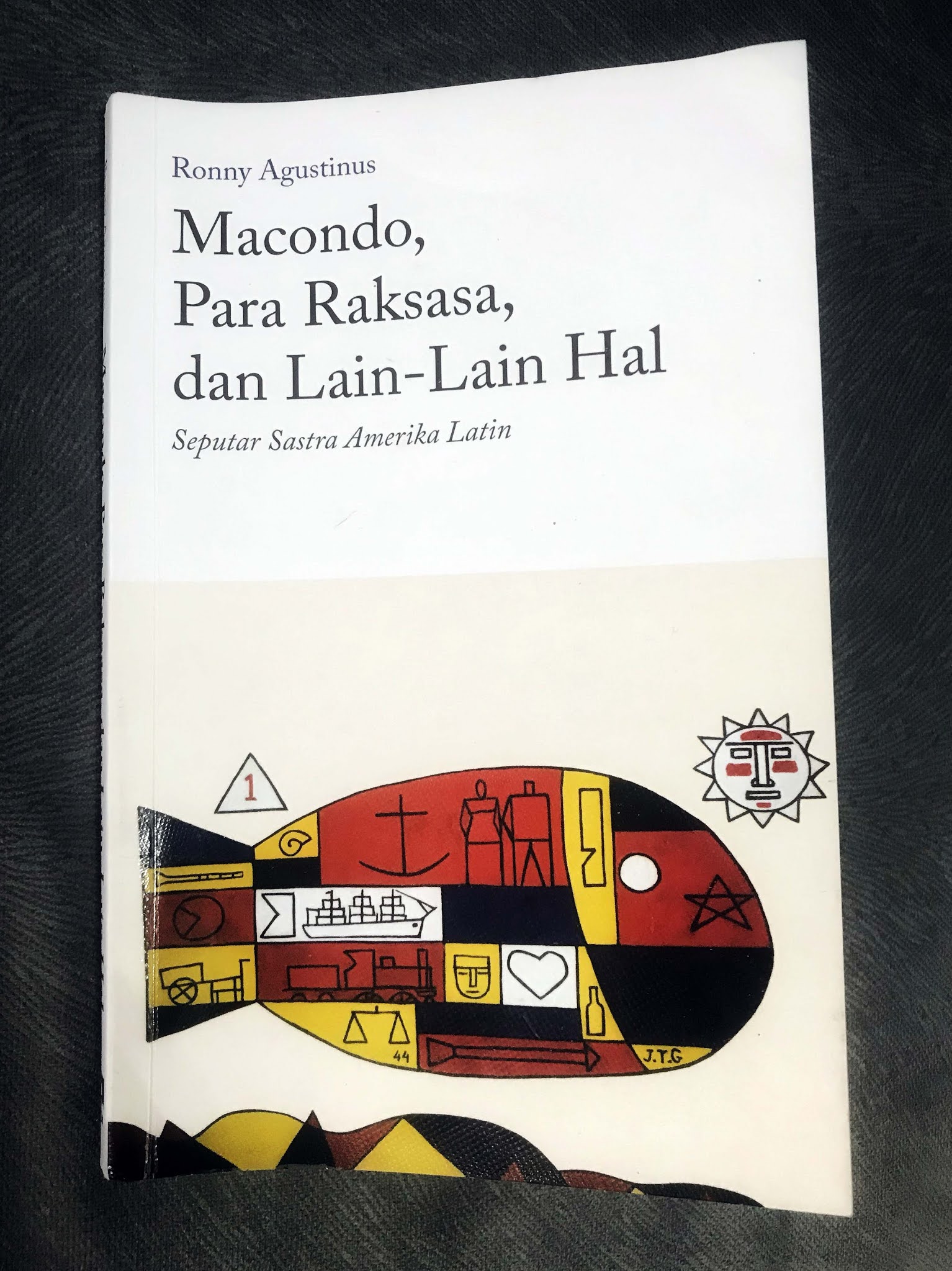 |
Adegan perkelahian dua raksasa sastra Amerika Latin itu, adalah bagian yang paling menarik bagi saya, dari buku Macondo, Para Raksasa, dan Lain-lain Hal, karya terkini Ronny Agustinus ini. Dalam catatan penerjemah teks sastra berbahasa Spanyol dan Pemimpin Redaksi penerbit Marjin Kiri itu, yang paling membuat penasaran dari tarikh permusuhan jangka panjang tersebut, baik Gabo maupun Mario, sama-sama bungkam tentang pokok pangkal permusuhan mereka. Kepada pers, teman-teman dekat, dan para penggemar. Karena itu, banyak orang hanya bisa menduga-duga. "Ini untuk apa yang kau katakan pada Patricia!" atau "Ini untuk apa yang kau lakukan pada Patricia!" begitu dua versi umpatan Mario Vargas saat ia meninju muka Gabo sebagaimana dikutip Ronny dari Garcia Marquez: A Life, buku yang ditulis oleh Gerald Martin, yang disebut-sebut sebagai biografi Marquez paling otoritatif karena berangkat dari hasil riset selama 17 tahun dan wawancara lebih dari 300 orang."Hanya Patricia LIosa yang tahu keseluruhan kisahnya," kata Gerald Martin.
Bila Gerald Martin membaca pangkal soal permusuhan Mario-Gabo dari campuran politik, seks, dan persaingan pribadi, Dasso Saldivar, penulis biografi Marquez yang lain, melihat persoalan di antara Gabo dan Mario itu semata-mata karena seks, atau yang dalam bahasa Ronny Agustinus; "Teman makan teman." Buku bertajuk Garcia Marquez; El Viaje a la Semilla yang ditulis Saldivar pada 1997 itu membuat klaim bahwa soal asmara dan perselingkuhanlah penyebab bersarangnya tinju Mario di wajah Gabo. Dinukilkan, si tampan Mario Vargas LIosa jatuh cinta pada seorang pramugari Swedia, dan karena itu ia sempat pindah ke Stockholm, meninggalkan Patricia, istrinya. Patricia kemudian meminta nasihat pada Garcia Marquez, dan ia menganjurkan agar Patricia menceraikan Mario. Klaim Saldivar itu disinyalir tidak didasarkan pada sumber-sumber yang valid, karena itu dianggap lebih dekat pada gosip ketimbang fakta. Mungkin itu pula sebabnya, biografi Marquez itu hanya terbit dalam bahasa Spanyol, dan tak diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain.
Sejatinya bukan tentang permusuhan yang tak kunjung tersingkap penyebabnya itu yang hendak dieksplorasi oleh Ronny Agustinus dalam bab 6 yang bertajuk Permusuhan Dua Raksasa dan Buku yang Baru Dicetak Ulang Setelah Setengah Abad itu, melainkan tentang persahabatan berusia sangat panjang, tentunya sebelum peristiwa penonjokan di Mexico City itu. Sedemikian akrabnya, Garcia Marquez, penulis magnum opus Seratus Tahun Kesunyian itu dengan novelis Peru, Mario Vargas LIosa, pemenang Nobel Sastra 2010, sampai-sampai ia menjadi Bapak Baptis dari putra Mario. Saat keduanya masih akur, Mario menulis sebuah buku penting berjudul Garcia Marquez: historia de un deicidio (Garcia Marquez; Sejarah Sang Pembunuh Allah), yang semula berbentuk disertasi doktoral di Universitas Compultense, Madrid, dengan judul Garcia Marquez; lengua y estructura de su obra narrativa (Garcia Marquez: Bahasa dan Struktur Karya Sastranya), yang mengantarkan kululusan Mario dengan predikat cum laude setelah persidangan 25 Juni 1971. Menurut Ronny, boleh jadi buku itu adalah analisis mendalam pertama atas kekaryaan Marquez, terutama untuk Cien anos de soledad (Seratus Tahun Kesunyian) yang sangat tersohor itu.
Dalam buku itu, Mario Vargas tidak hanya membedah aspek kekaryaan Marquez, tetapi juga membingkai rintisan teorinya sendiri tentang novel, yang kelak dikenal sebagai total novel. Bagi Vargas, novel adalah sebuah dunia yang utuh, dan kerja seorang novelis adalah membangun dunia dan kenyataan di dalamnya, atas dasar ketidakpuasannya terhadap dunia yang dihuninya sekarang. Dalam kerja membangun dunia itu, novelis menggantikan kekuasaan Tuhan, atau dalam istilah Ronny Agustinus, ia membunuh keilahian (hal. 66). Dalam analisa tekstualnya, Vargas menyingkap "rahasia" realisme-magis Garcia Marquez sebagai imajinasi komunal masyarakat tropis Amerika Latin yang cenderung melebih-lebihkan kisah sejarah dengan gambaran-gambaran tertentu, misalnya, bagaimana pada masa boom karet di Amazon, para penyadap kulit putih konon menyalakan cerutu dengan membakar uang kertas. Gambaran yang berlebihan, tapi justru melekat di benak masyarakat dan dituturkan dari generasi ke generasi. Menurut Mario, teknik inilah yang kemudian digunakan oleh Gabo dalam Seratus Tahun Kesunyian, yakni berbohong dan menggombal sedemikian rupa sehingga orang menjadi yakin. Marquez sendiri kerap mengatakan bahwa ia butuh bertahun-tahun untuk mencari teknik yang tepat untuk Seratus Tahun Kesunyian. Ia selalu ingin meniru cara neneknya mendongeng. Ia tahu cerita neneknya, tak ada yang benar dan sesuai kenyataan, tapi bisa membuat pendengar percaya (hal.68).
"Tak ada satu teori yang konsisten mengenai realisme-magis," kata akademisi sastra William Rowe, sebagaimana dikutip Ronny pada bab bertajuk Mengenang Gabriel Garcia Marquez, Novelis-Jurnalis, untuk memastikan sedemikian terbukanya kemungkinan dalam melanjutkan perdebatan tentang genre baru yang menandai era Boom sastra Amerika Latin yang sangat melekat pada corak kekaryaan Garcia Marquez. "Untuk gampangnya, katakanlah realisme-magis itu sebagai cara menghadirkan yang magis sebagai unsur yang lumrah dalam realitas keseharian," kata Ronny. Sebagai misal, bayi yang lahir dengan ekor babi, montir yang selalu diikuti kupu-kupu, tulang-belulang gadis muda dengan rambut puluhan meter di tengkoraknya dan sederet karakter ajaib lain yang tiada duanya dalam jagat kesusastraan. Namun, persenyawaan antara yang riil dan yang magis dalam karya-karya Gabo atau dalam kebanyakan teks sastra Amerika Latin, bukan imaji kosong belaka, melainkan perlu dibaca dalam konteks sosial-politik negara pascakolonial. Dalam mahakarya Seratus Tahun Kesunyian, temuan-temuan saintifik yang dihadirkan oleh modernitas (magnet, kereta api, piringan hitam) dianggap magis oleh penduduk pribumi desa Macondo. Sementara hantu-hantu dan orang yang bisa melayang (yang mereka anggap lumrah) justru akan dianggap magis oleh pembaca modern. (hal.72).
Gabriel Garcia Marquez, sastrawan Kolombia kelahiran Aracataca 6 Maret 1927, pemenang Nobel Sastra 1982, dan Mario Vargas LIosa, sastrawan Peru kelahiran 28 Maret 1936, pemenang Nobel sastra 2010, adalah dua nama penting di era Boom sastra Amerika Latin yang menurut catatan buku ini bermula sejak 1960-an. Boom yang dimaksud dapat merujuk pada lonjakan penerbitan, penjualan dan pembacaan publik atas karya-karya sastra Amerika Latin, baik dalam bahasa Spanyol maupun terjemahannya di dunia global. Internasionalisasi dari distribusi kekaryaan yang berlangsung sampai era 1970-an itu secara mencolok membedakan dirinya dari generasi sebelumnya. "Sebelum tahun 1960, tidak lazim mendengar orang bicara tentang novel Amerika Latin kontemporer, " kata penulis Cile Jose Donoso dalam memoar bertajuk Historia personal del "boom" (1972) sebagaimana dikutip Ronny dalam bab bertajuk El Boom dan Fiksi Amerika Latin Sesudahnya. Adapun karya-karya yang termasuk ke dalam kanon Boom ini antara lain: Lamuerte de Artemio Cruz (1962) oleh Carlos Fuentes (Meksiko), La ciudad y los perros (1962) oleh Mario Vargas LIosa (Peru), Rayuela (1963) oleh Julio Cortazar (Argentina), La casa Verde (1966) oleh Mario Vargas LIosa, dan Cien anos de soledad (1967) oleh Gabriel Garcia Marquez (Kolombia).
Yang menarik dari pemetaan yang dilakukan Ronny dalam buku ini adalah dimensi politik sebagai faktor pemicu internasionalisasi karya-karya dari Amerika Latin itu, yaitu Revolusi Kuba 1959. Sebelum Revolusi Kuba, orang hanya bicara novel Uruguay atau novel Ekuador, novel Meksiko atau Venezuela, di mana novel tiap negara terkurung dalam batas-batas teritorial negaranya. Ketenaran sebuah karya, dalam banyak kasus hanya menjadi perkara lokal saja. Kondisi itu berubah jauh sejak meletusnya Revolusi Kuba. Kemenangan Fidel Castro membuat negara-negara Amerika Selatan mulai melihat diri mereka sebagai satu kesatuan politik yang mengalami rute historis serupa. Dukungan pada Castro menyatukan kaum intelektual di negara-negara Amerika Selatan dan menumbuhkan rasa sebagai satu Amerika Latin. Dalam sebuah Kongres intelektual di Copcepcion, Cile 1962, secara provokatif, novelis Meksiko Carlos Fuentes mengatakan "di Amerika Latin, sastra dan politik tak terpisahkan."(hal.6). Menurut Ronny, semangat itu pula yang membuat karya-karya di era Boom ini menjadi sangat politis dengan caranya masing-masing dalam mempersoalkan kediktatoran politik; Cortazar dengan kepelikan urbannya, Fuentes merunut sejarah politik Meksiko, Vargas LIosa menyoal struktur penindasan dan militerisme, Garcia Marquez menggunakan realisme-magis dengan cara yang politis dalam melihat sejarah kolonialisme dan modernisasi Amerika Latin secara keseluruhan. (hal.7)
Khususnya tentang Seratus Tahun Kesunyian mahakarya Gabriel Garcia Marquez yang sangat familiar di Indonesia sejak 1980-an, buku setebal 165 halaman ini, seperti hendak menambah kedalaman galian publik pembaca tanah air, yang semula hanya berputar-putar sekitar terma "realisme-magis" sebagai keterampilan artistik khas Amerika Latin yang digagas Gabo, ke wilayah identifikasi tentang substansi yang terkandung dalam karya besar itu. "Jangan lupa," kata Ronny, bahwa tema inti Seratus Tahun Kesunyian adalah pembantaian terhadap 3000 buruh perkebunan pisang yang dilakukan tentara lewat berondongan senapan mesin. Jose Arcadio Segundo, yang selamat dari maut, terperanjat mendapati kenangan akan pembantaian itu dari ingatan warga. Pemerintah menghapusnya dari sejarah resmi, sementara hujan deras bertahun-tahun menghapuskan bukti-bukti fisik dari peristiwa besar itu. Arcadio menghabiskan sisa umurnya untuk melestarikan kenangan akan 3000 korban tewas itu. (hal. 78)
Buku ini juga menyebut lembaga penerbitan dan peran agen sastra yang bermarkas di Barcelona, Spanyol, yang berjasa besar dalam mengantarkan karya-karya dari Amerika Latin kepada pembaca Eropa dan dunia, termasuk Indonesia. Carmen Balcells disebut sebagai agen sastra yang berperan besar menawarkan karya-karya Amerika Latin kepada penerbit-penerbit besar dunia. Ia dikenal keras dan kontroversial karena menuntut oplah cetak yang tinggi. Sementara Carlos Barral yang dikenal sebagai penyair ternama, dianggap berhasil menjadikan Seix Barral sebagai penerbit buku sastra bergengsi dengan memberikan anugerah-anugerah sastra pada masa itu. Menurut catatan Ronny, beberapa pengamat bahkan memakai anugerah sastra Biblioteca Breve yang diberikan oleh penerbit Seix Barral sebagai patokan untuk menandai awal dan akhir era Boom (hal.8) Khusus tentang jasa besar agen sastra Carmen Balcells, Ronny membahasnya secara panjang lebar dalam satu bab khusus yang bertajuk Carmen Balcells: Di Balik Layar El Boom.
Selain mengajak pembaca untuk berselancar lebih jauh ke dalam khazanah sastra Amerika Latin, buku ini juga tampak hendak meluruskan beberapa sesat pikir tentang keudikan orang-orang Macondo (desa fiktif dalam Seratus Tahun Kesunyian yang kerap menjadi nama lain dari "realisme-magis"), yang kemudian direspons secara kritis oleh generasi penulis baru Amerika Latin dengan gerakan yang dinamai MacOndo (gabungan dari McDonald's, Macintosh, dan Condominium, untuk menyebut situasi kultural Amerika Latin abad 21). McCondo dicetuskan pada 1996, oleh penulis Cile, Alberto Fuguet dan Sergio Gomez dalam antologi cerpen 18 penulis muda dengan judul yang sama. Buku itu sengaja diluncurkan di salah satu cabang McDonald's di kota Santiago, Cile. Setelah peluncuran antologi itu, Newsweek dan The Observer menurunkan laporan utama tentang lahirnya generasi baru sastra Amerika Latin dan memproklamirkan berakhirnya era "realisme-magis."
Bagi Ronny, McCondo tak lebih dari ingar bingar khas peralihan abad lalu, masa-masa yang dipenuhi eforia "kapitalisme sebagai akhir sejarah," ledakan teknologi informasi, janji-janji globalisasi dan ekonomi baru yang diusung Amerika Serikat. Lewat buku ini, Ronny agaknya tidak ingin melupakan tradisi Macondo begitu saja, apalagi membenarkan bahwa pengaruh Boom telah pudar dengan sendirinya, seiring datangnya zaman baru. "Pablo Neruda sering mengatakan bahwa setiap penulis Amerika Latin berjalan sambil menyeret raga yang berat; raga masyarakatnya, raga masa lalunya. Dan, Carlos Fuentes pun kemudian mempertegasnya; kita harus mengasimilasi beban berat masa lalu agar kita tidak lupa pada apa yang telah memberi kita hidup... (hal 25).
Dengan begitu, meski setelah era Boom bermunculan generasi baru seperti Isabel Allende, Antonio Skarmeta, Osvaldo Soriono, dan Luis Sepulveda, bagi Ronny, masa lalu tak pernah mati di Amerika Latin, dan tegangan sejarah itulah (antara masa lalu yang bergelimang penindasan dan masa depan yang dirundung kemiskinan) yang memberi penulis Amerika Latin daya hidup. Barangkali inilah yang membuat kita di Indonesia, merasa dekat dengan konteks sosial-politis negara-negara di Amerika Latin. Meski kita tak punya tradisi sastra Macondo atau "realisme-magis" yang dapat memetakan betapa beratnya beban masa silam itu dengan cara yang ajaib, bangsa kita pun bagai terombang-ambing di antara beban berat akibat kediktatoran masa lalu (termasuk penindasan yang dilakukannya,) dengan kemiskinan, bahkan kepandiran di masa kini dan masa depan...
DATA BUKU
Penulis. : Ronny Agustinus
Penerbit: Tanda Baca, Yogyakarta, Juni 2021
Tebal. : 166 Hal


Comments